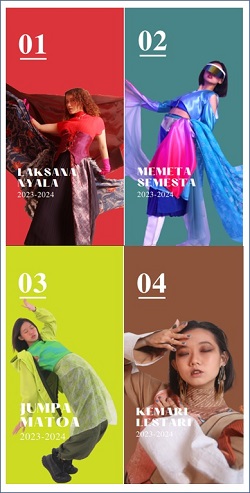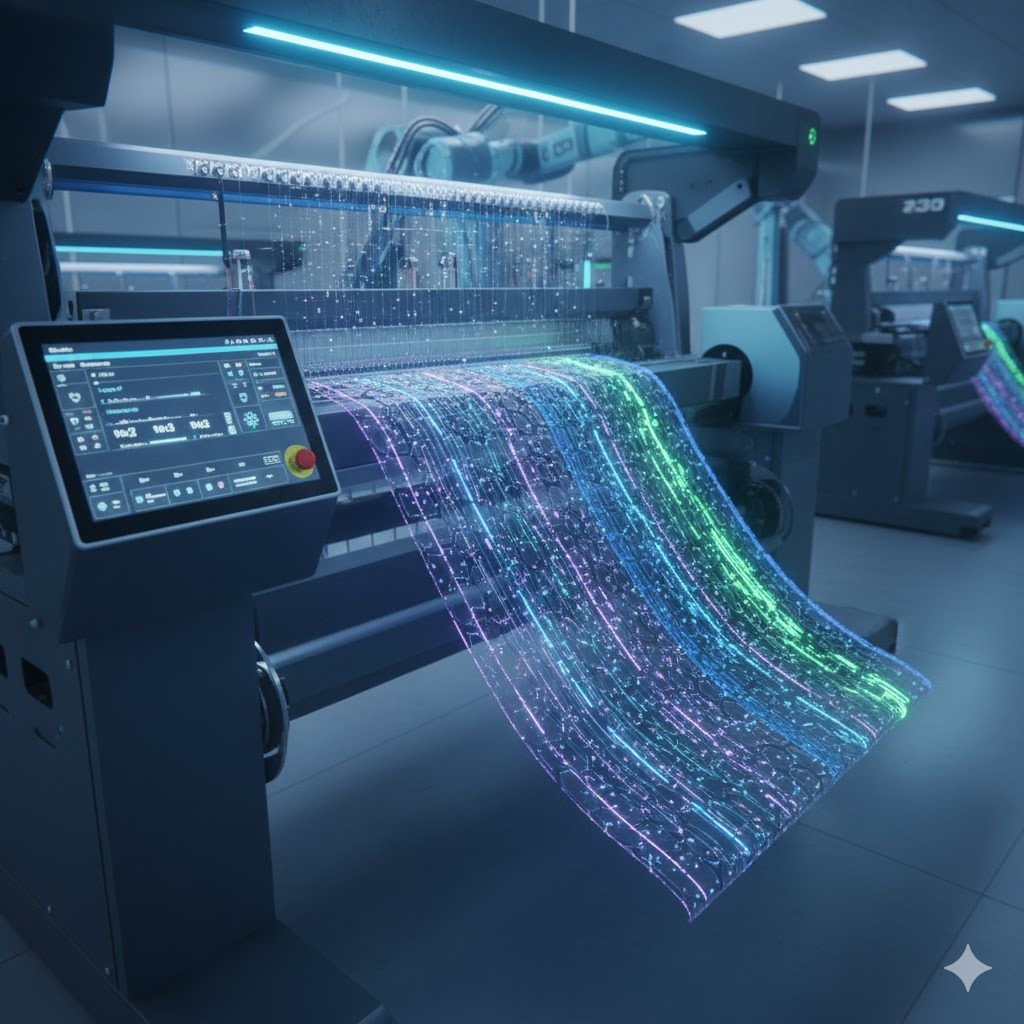Untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi, surplus perdagangan Tiongkok telah menembus angka $1 triliun dalam sebelas bulan pertama tahun 2025. Pencapaian ini bukan sekadar kemenangan angka bagi Beijing; ini adalah sinyal mendalam mengenai pergeseran struktural ekonomi global yang meningkatkan ketegangan dari Washington hingga Brussel. Rekor surplus yang naik 3,6 persen secara tahunan ini mengungkap narasi kompleks tentang sebuah negara yang telah menguasai produksi teknologi tinggi, namun di saat yang sama berjuang meyakinkan rakyatnya sendiri untuk berbelanja.
Di jantung angka pemecah rekor ini terdapat kontradiksi internal yang tajam: mesin manufaktur yang bekerja dengan kecepatan penuh di tengah latar belakang permintaan domestik yang stagnan. Penurunan pasar properti dan ketidakpastian lapangan kerja di Tiongkok telah memaksa rumah tangga mereka untuk memperketat ikat pinggang. Hal ini memicu fenomena yang disebut para ekonom sebagai "vent-for-surplus." Dalam skenario ini, produsen Tiongkok yang tidak mampu menjual kelebihan barangnya di dalam negeri, mengalihkan output masif mereka ke pasar luar negeri. Banjir barang ini semakin diperparah oleh jatuhnya harga domestik dan nilai tukar renminbi yang relatif lemah, membuat ekspor Tiongkok sangat murah bagi pembeli internasional, namun menghambat impor yang seharusnya bisa menyeimbangkan neraca perdagangan.
Meski Barat sering memandang Tiongkok sebagai pusat perakitan barang kelas bawah, data tahun 2025 menunjukkan lompatan canggih menuju rantai nilai manufaktur yang lebih tinggi. Tiongkok kini memimpin dalam 66 dari 74 teknologi kritis—sebuah keunggulan teknologi yang mendorong ekspor galangan kapal naik hampir 27 persen. Dominasi pada industri maju ini memungkinkan Tiongkok mengirimkan produk spesifikasi tinggi dengan harga yang tidak mungkin ditandingi oleh pesaing. Bahkan sektor tekstil dan pakaian jadi tradisional, yang lama dianggap sebagai "pemain lama," telah mengalami metamorfosis teknologi tinggi. Dengan investasi besar pada otomatisasi dan kain fungsional, Tiongkok telah bergeser dari sekadar menjahit pakaian menjadi penyedia bahan antara (intermediate) seperti benang dan kain yang sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik di Vietnam dan Bangladesh.
Mungkin manuver strategis paling signifikan yang terlihat di tahun 2025 adalah keberhasilan Tiongkok beralih dari ketergantungan pada Amerika Serikat. Meskipun pengiriman ke pasar Amerika anjlok hampir 18 persen akibat tarif yang tinggi, total ekspor Tiongkok tidak goyah. Sebaliknya, Beijing secara agresif melakukan diversifikasi ke kawasan Global South. Ekspor ke Afrika melonjak 26 persen, sementara blok ASEAN—yang kini menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok—mencatat kenaikan 13,7 persen. Lebih jauh lagi, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam telah muncul sebagai "pusat penghubung" (connector hubs), di mana komponen asal Tiongkok diselesaikan prosesnya sebelum dikirim kembali ke pasar Barat untuk menghindari hambatan perdagangan langsung.
Namun, pencapaian $1 triliun ini datang dengan label peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang menyebut ketidakseimbangan saat ini "tidak berkelanjutan." Seiring dengan proyeksi pangsa ekspor global Tiongkok yang akan mencapai 16,5 persen pada tahun 2030, tekanan bagi Beijing untuk menyeimbangkan ekonominya dengan menggenjot konsumsi internal mencapai titik kritis. Tanpa kebangkitan permintaan rumah tangga domestik atau penguatan nilai tukar mata uang, dunia mungkin akan segera menyaksikan era proteksionisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk saat ini, Tiongkok tetap menjadi raksasa manufaktur global, namun rekor surplusnya menjadi pengingat keras bahwa ekonomi yang hanya menjual tanpa pernah membeli berisiko memicu gesekan perdagangan global yang tidak bisa diredam hanya dengan keunggulan teknologi.
Jakarta, 18 Desember 2025
REDAKSI