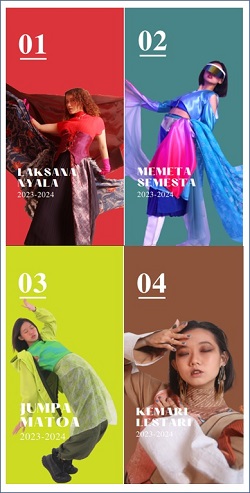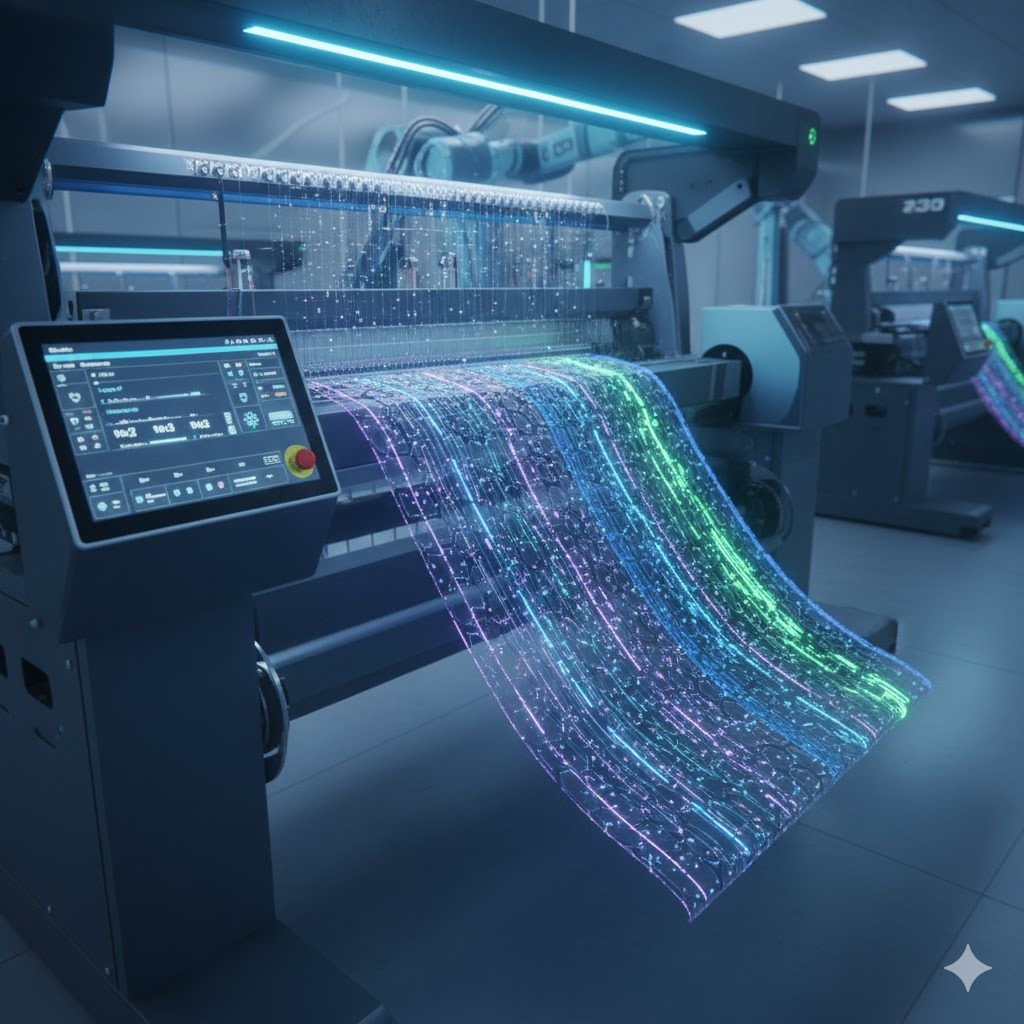Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyampaikan aspirasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk memperluas cakupan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri, termasuk sektor tekstil. Hal ini dipandang penting mengingat industri tekstil saat ini harus membayar gas bumi dengan harga mencapai US$14 per metric british thermal unit (MMBTU), sementara dengan program HGBT, biaya tersebut dapat ditekan hingga US$6 per MMBTU.
Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif, menegaskan bahwa harga gas murah sangat dibutuhkan untuk mendukung proses produksi dan meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global. "Negara-negara pesaing kita membayar gas dengan harga sekitar US$6 per MMBTU, sedangkan industri kita membayar US$14 untuk komersial dan US$7 untuk industri umum," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Peran Gas dalam Sektor Industri Tekstil
Industri tekstil terdiri dari tiga sektor utama: industri hulu (upstream) yang memproduksi serat dan benang, industri tengah (midstream) yang mengolah bahan setengah jadi seperti pemintalan benang dan kain, dan industri hilir (downstream) yang memproduksi pakaian jadi siap pakai. Sebagai bagian hilir, industri tekstil memerlukan gas bumi untuk proses produksinya. Namun, dengan harga gas yang tinggi, banyak pelaku industri terpaksa mengimpor bahan baku karena lebih ekonomis.
"Gas menjadi komponen utama agar industri dapat bersaing. Tanpa gas murah, sektor midstream harus mengandalkan impor bahan baku," kata Ian. Oleh sebab itu, API mendesak pemerintah memperluas program HGBT untuk mencakup industri tekstil sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kinerja sektor ini.
Tantangan Impor dan Kebijakan Non-Tarif
Selain masalah harga gas, API juga menyoroti tantangan besar lainnya yang dihadapi industri tekstil, yaitu maraknya impor, baik legal maupun ilegal, terutama dari Tiongkok. Ian mengungkapkan bahwa gas mahal dan produk impor yang lebih murah membuat produk tekstil buatan Indonesia sulit bersaing.
"Negara lain memiliki ribuan kebijakan perlindungan dagang berupa non-tariff barriers, sementara Indonesia hanya memiliki sekitar 350 kebijakan," jelas Ian. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa memiliki regulasi ketat yang melindungi pasar domestik mereka, sehingga Indonesia kesulitan menembus pasar mereka. Dengan jumlah kebijakan non-tarif yang minim, pasar Indonesia rentan diserbu produk impor.
Dampak Utilisasi Rendah dan Ancaman PHK
Dampak dari tantangan ini sangat terasa pada utilisasi kapasitas produksi industri tekstil yang hanya mencapai 40-50%. Ian mengungkapkan, rendahnya kapasitas produksi ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat, sekitar 240 ribu pekerja di sektor tekstil terkena PHK sejak pandemi 2020 hingga 2024. Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menambahkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang memadai, industri tekstil terancam terus merugi dan kehilangan daya saing.
"Saat ini, ada dua industri tekstil besar yang diperkirakan akan menyusul pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berbasis di Surakarta," ungkap Danang. Walaupun ia tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut, ia menekankan bahwa situasi ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa kejayaan industri tekstil Indonesia sedang merosot.
Refleksi Kejatuhan Industri Tekstil
Danang mengingatkan bahwa kejadian ini mencerminkan kemunduran industri tekstil yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia tiga dekade lalu. "Contoh industri besar seperti Texmaco dulu merepresentasikan kekuatan tekstil Indonesia di Asia. Kini, sektor ini harus berjuang untuk kembali bangkit," ujarnya.
Untuk menghadapi situasi ini, API mendesak pemerintah untuk mengadopsi langkah-langkah strategis dalam memperluas HGBT dan memperkuat kebijakan proteksi pasar, sehingga industri tekstil dapat kembali berdaya saing dan melindungi tenaga kerja di sektor padat karya ini.