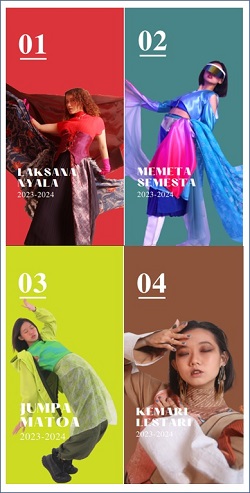Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, bahkan sebelum kabar kesulitan yang dialami PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mencuat ke publik. Sektor ini, yang dahulu menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, kini harus berjuang keras melawan berbagai tekanan eksternal dan internal. Salah satu penyebab utama adalah minimnya keberpihakan pemerintah terhadap industri tekstil, yang membuatnya sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar.
Akibatnya, industri tekstil semakin kehilangan daya saing, terhimpit oleh tekanan pasar global, dan menyusutnya kemampuan finansial. Dampak terbesar dirasakan oleh tenaga kerja, mengingat sektor ini merupakan industri padat karya yang menyerap jutaan pekerja. Namun, alih-alih melakukan intervensi strategis untuk membangun daya saing industri, pemerintah sering kali justru mengambil kebijakan yang tidak menyentuh inti masalah.
Kebijakan Larangan Pakaian Bekas: Solusi atau Distraksi?
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Upaya ini gencar dilakukan dengan penegakan aturan hingga pembakaran pakaian bekas impor sebagai bentuk kampanye. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan. Pasar domestik tetap menunjukkan permintaan tinggi untuk pakaian bekas, menandakan bahwa kebijakan tersebut sulit diterapkan secara efektif.
Lebih jauh, larangan pakaian bekas dinilai tidak menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi industri tekstil. Tantangan terbesar justru datang dari tingginya volume impor tekstil, terutama dari China dan negara lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata Indonesia mengimpor 2,25 juta ton produk tekstil per tahun dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, volume ini bahkan meningkat 21,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Deindustrialisasi Prematur dan Penurunan Daya Saing
Persoalan inti dari industri tekstil nasional adalah pelemahan daya saing dibandingkan negara-negara tetangga. Industri tekstil Indonesia menghadapi gelombang deindustrialisasi prematur, yaitu penyusutan sektor manufaktur sebelum mencapai kematangan yang seharusnya. Situasi ini diperburuk oleh tekanan resesi global pascapandemi yang menyebabkan penurunan permintaan di pasar ekspor.
Di sisi lain, tingginya impor produk tekstil menciptakan persaingan berat bagi produsen lokal di pasar domestik. Kondisi ini membuat industri tekstil nasional kesulitan mengembangkan kapasitas dan berinovasi untuk tetap kompetitif.
Strategi Penyelamatan yang Diperlukan
Untuk menyelamatkan industri tekstil nasional, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang lebih menyentuh akar masalah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:
Meningkatkan Daya Saing Industri Lokal
Pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong modernisasi teknologi di sektor tekstil, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan sumber daya manusia.
Pengendalian Impor Tekstil
Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk membatasi impor tekstil yang tidak sesuai standar dan mendorong konsumsi produk lokal.
Diversifikasi Pasar
Perusahaan tekstil nasional harus didorong untuk menjajaki pasar-pasar baru selain pasar tradisional, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu pasar tertentu.
Kolaborasi dengan Pelaku Industri
Pemerintah perlu berkolaborasi dengan pelaku industri untuk merancang kebijakan berbasis kebutuhan sektor, seperti pengurangan beban pajak dan penyediaan akses pendanaan yang lebih mudah.
Promosi Kampanye Cinta Produk Lokal
Mengedukasi masyarakat untuk memilih produk tekstil dalam negeri adalah langkah penting untuk mendorong permintaan domestik terhadap produk lokal.
Penyelamatan industri tekstil membutuhkan komitmen serius dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, sektor ini dapat kembali menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, sekaligus menyerap tenaga kerja secara signifikan. Tanpa langkah strategis, industri tekstil hanya akan menjadi kenangan sebagai sektor yang pernah berjaya.