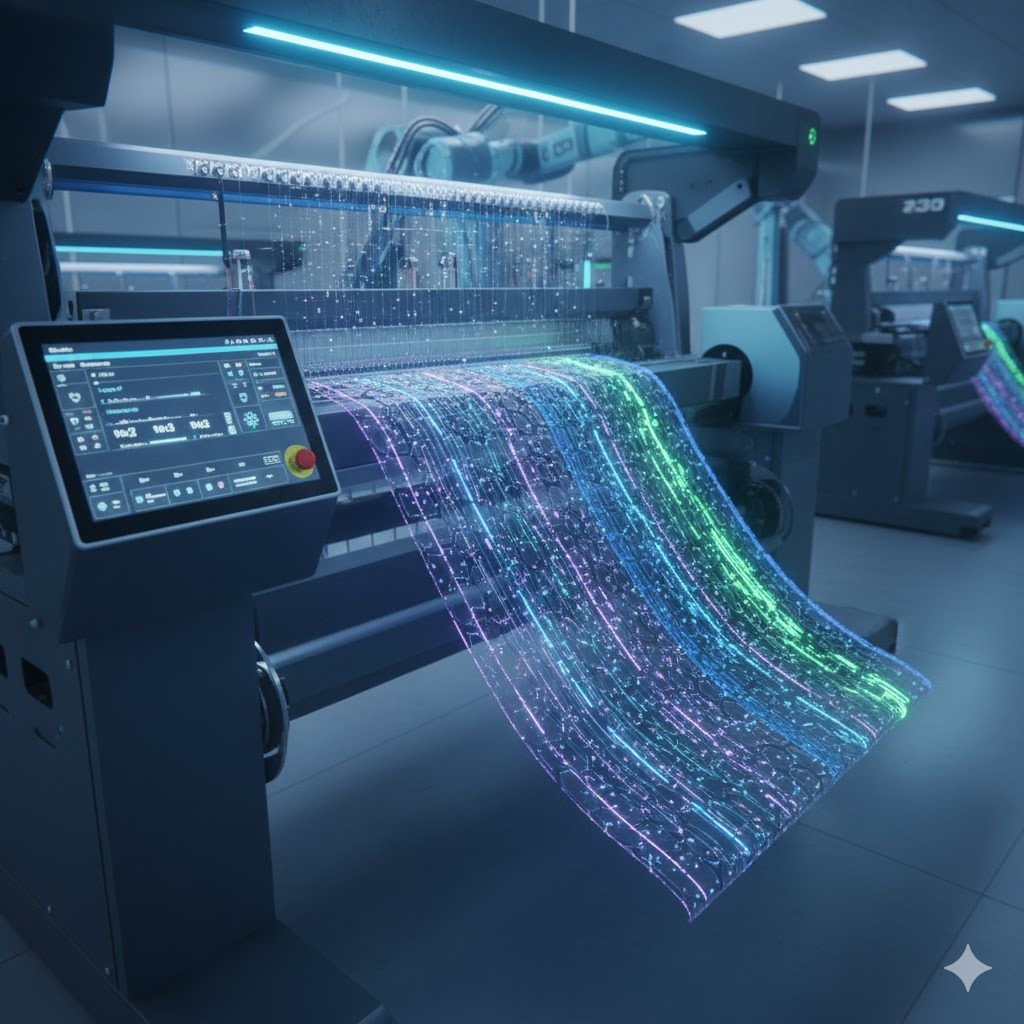Tak lama setelah perayaan Idul Fitri 2025, Zuhri, seorang pekerja pabrik tekstil di Semanan, Jakarta Barat, harus menerima kenyataan pahit: ia terkena pemutusan hubungan kerja. Kontraknya tak lagi diperpanjang karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan efisiensi akibat tekanan berat yang menghantam industri tekstil dalam negeri. Zuhri tidak terkejut. Ia sudah lama menyadari bahwa sektor ini tengah megap-megap menghadapi tantangan berat, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tekstil impor murah dari China terus membanjiri pasar domestik, membuat produk lokal tak mampu bersaing secara harga. Situasi ini diperparah oleh perang tarif yang digulirkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan AS menaikkan tarif impor produk tekstil asal Indonesia hingga 47% dipandang sebagai pukulan telak bagi eksistensi industri tekstil nasional yang kini di ujung tanduk.
Kendati tidak semua produk dikenai tarif maksimal, lonjakan bea masuk tetap menjadi momok serius. Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa kenaikan tarif bergantung pada jenis produk, namun sebagian besar kini harus menghadapi tambahan bea masuk hingga 10% dari tarif dasar sebelumnya. Imbasnya pun nyata: Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Tanah Air, gulung tikar dan mem-PHK lebih dari 10 ribu pekerja. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia memperkirakan akan ada 10 perusahaan lagi yang terancam menyusul.
Kondisi ini menguak kelemahan struktural industri tekstil Indonesia yang telah lama bergantung pada tenaga kerja murah dan minim inovasi. Menurut pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, krisis ini bukan semata dampak kebijakan luar negeri, melainkan akibat dari lemahnya fondasi industri itu sendiri. Meski demikian, ia menilai pemerintah tak bisa hanya berpangku tangan.
Usulan pun mengemuka, mulai dari negosiasi tarif dagang dengan AS, kerja sama strategis di sektor mineral penting, hingga insentif bagi perusahaan AS yang mau memindahkan pabrik ke Indonesia. Pemerintah disebut telah menyiapkan skema penyederhanaan regulasi sebagai upaya menarik investor. Namun, efektivitas lobi-lobi yang dilakukan, termasuk melalui ASEAN, dipertanyakan mengingat forum kawasan itu dinilai lebih banyak bicara ketimbang bertindak nyata.
Serikat pekerja pun mendesak pemerintah untuk lebih agresif dalam melindungi produsen tekstil nasional. Apalagi, ancaman limpahan produk dari negara-negara lain yang juga dikenai tarif tinggi AS bisa membanjiri pasar domestik. Jika tidak ada tindakan protektif, gelombang PHK yang lebih besar bukan tidak mungkin terjadi.
Ironisnya, di tengah badai krisis ini, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor tekstil Indonesia pada 2024 justru mencatat sedikit kenaikan. Nilai ekspor mencapai US$9,85 miliar atau naik 0,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Volume ekspor pun naik 5,06%. Namun, angka tersebut belum cukup menjadi pelipur lara bagi ribuan pekerja seperti Zuhri yang kehilangan mata pencaharian.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan pelaku industri untuk segera melakukan transformasi menyeluruh. Jika tidak, industri tekstil Indonesia akan terus terjepit di antara tekanan global dan kelemahan internal yang belum juga diselesaikan.