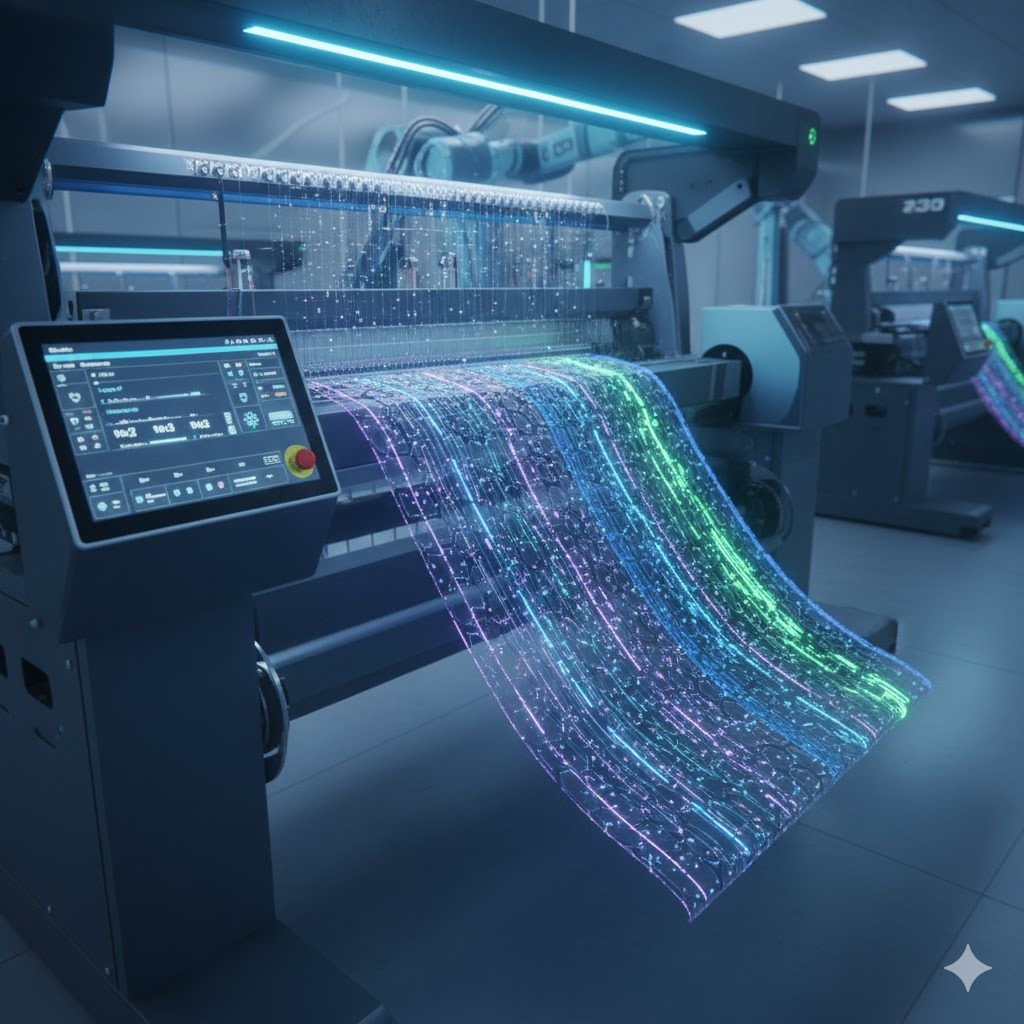Kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif tambahan sebesar 32% untuk seluruh produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025 menjadi kabar buruk bagi sektor industri nasional. Keputusan sepihak yang diumumkan oleh Presiden Donald J. Trump ini dinilai sebagai pukulan telak, khususnya bagi sektor tekstil dan alas kaki yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.
Pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa tarif tinggi tersebut dapat mengguncang stabilitas ekonomi dalam negeri. Sebanyak 3,6 juta pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor padat karya ini terancam kehilangan pekerjaan jika ekspor ke AS anjlok secara drastis. Selain itu, pelaku industri pun mulai menghadapi risiko pemutusan kontrak dari pembeli global yang kini melirik negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja yang menawarkan tarif ekspor lebih rendah.
Kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan industri, tapi juga memperbesar risiko pengangguran dan melemahkan daya beli masyarakat. Lebih jauh lagi, target surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$40 miliar pada tahun 2025 diperkirakan akan meleset, mengingat lebih dari 10% ekspor non-migas selama ini diserap oleh pasar Amerika Serikat. Lonjakan tarif otomatis akan menurunkan volume ekspor, memangkas pemasukan devisa, dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Dampak lainnya juga terasa terhadap program hilirisasi nasional. Menurut Achmad, investor asing akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia jika hasil produksi mereka akan dikenai tarif tinggi saat memasuki pasar global. Margin ekspor yang tergerus membuat Indonesia kehilangan daya tarik sebagai basis produksi.
Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Apindo, Didit Ratam, turut memperkuat kekhawatiran ini. Ia menyebutkan bahwa nilai ekspor tekstil dan produk tekstil ke AS mencapai sekitar US$4 miliar, sementara alas kaki menyumbang sekitar US$3 miliar. Jika beban tarif ini benar-benar diberlakukan, dampaknya akan sangat terasa terhadap industri dan pekerjanya.
Apindo memang melihat perluasan pasar ke negara non-tradisional sebagai opsi jangka menengah, namun langkah tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untuk itu, Didit mendorong agar pemerintah segera memberikan berbagai bentuk dukungan nyata guna menyelamatkan sektor padat karya ini.
Beberapa langkah yang diajukan antara lain penghapusan iuran Jaminan Pensiun sebesar 2% yang dianggap tumpang tindih dengan iuran JHT sebesar 3,5%, serta permintaan agar pemerintah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan masa transisi. Usulan ini merujuk pada kebijakan serupa saat masa pandemi COVID-19 lalu.
Apindo juga meminta agar pemerintah menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan baku impor dan biaya subkontrak yang selama ini menekan arus kas industri. Dalam situasi tekanan global seperti ini, dukungan fiskal dan non-fiskal dari pemerintah menjadi penentu utama apakah industri padat karya dapat bertahan atau justru tumbang.