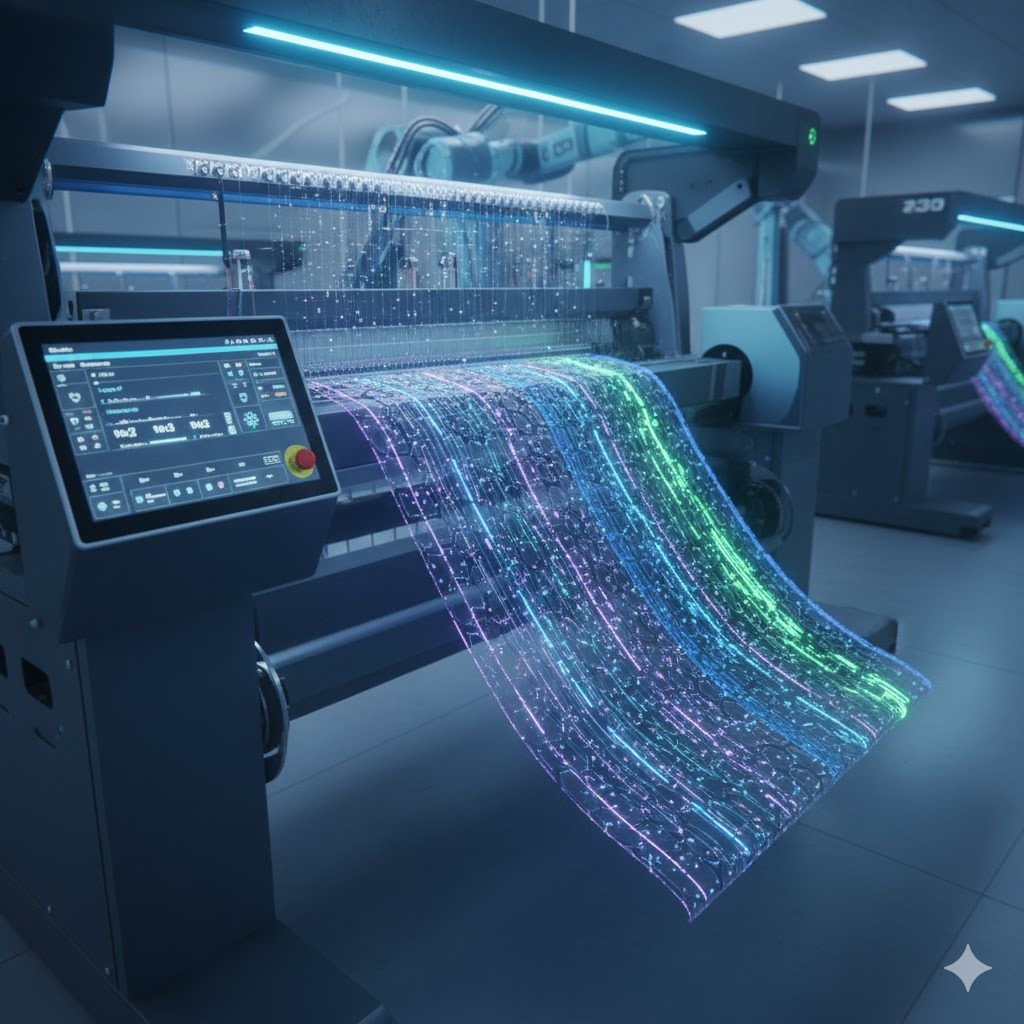Kebijakan tarif ekspor baru Amerika Serikat yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang menimbulkan kecemasan besar bagi jutaan buruh tekstil di Asia. Kamboja dan Sri Lanka, dua negara penghasil pakaian utama untuk merek global seperti Nike, Levi's, dan Lululemon, akan dikenakan tarif tinggi masing-masing sebesar 36% dan 30%. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja, terutama perempuan, yang mendominasi tenaga kerja di sektor tersebut.
Di Kamboja, seorang buruh bernama Nao Soklin mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Bersama suaminya, ia bekerja menjahit tas selama 10 jam sehari dengan penghasilan sekitar US$570 per bulan, jumlah yang nyaris tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar keluarga mereka. Seruan agar Presiden Donald Trump mencabut tarif ekspor pun disampaikan langsung oleh para buruh, yang merasa hidup mereka berada di ujung tanduk.
Kamboja dan Sri Lanka memang sangat bergantung pada ekspor tekstil ke pasar Amerika. Industri ini menjadi penyumbang devisa penting dan menyediakan lapangan kerja bagi ratusan ribu orang. Di Kamboja, industri tekstil mempekerjakan lebih dari 900.000 orang dan menyumbang lebih dari sepersepuluh total ekspor nasional. Sementara di Sri Lanka, sektor ini menghasilkan pendapatan ekspor sebesar US$1,9 miliar pada 2024.
Pemerintah kedua negara tengah berupaya melakukan negosiasi ulang dengan AS demi mendapatkan keringanan tarif. Namun, hasilnya masih belum pasti. Di sisi lain, para analis menilai kebijakan tarif ini justru mengabaikan keuntungan besar yang selama ini dinikmati perusahaan-perusahaan AS dari akses ke tenaga kerja murah di negara berkembang. Sistem perdagangan yang dulunya memberi ruang bagi pertumbuhan negara-negara kecil kini berubah menjadi hambatan.
Beban terberat dari kebijakan ini akan ditanggung oleh perempuan. Sebagian besar buruh tekstil di Sri Lanka dan Kamboja adalah perempuan yang bekerja untuk menafkahi keluarga besar dengan gaji minimum. Jika pabrik mulai tutup karena biaya ekspor yang tinggi, banyak dari mereka berisiko kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, bahkan kesulitan memberi makan anak-anak mereka.
Sejumlah buruh bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke negara tetangga seperti Thailand demi mencari pekerjaan, meski harus menempuh jalur ilegal. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain selain terus berharap pada perubahan kebijakan. Mereka menyampaikan harapan mereka dengan tulus: agar dunia, termasuk pemimpin negara besar seperti AS, bisa melihat penderitaan mereka dan mempertimbangkan kembali dampak nyata dari kebijakan ekonomi terhadap rakyat kecil di negara berkembang.