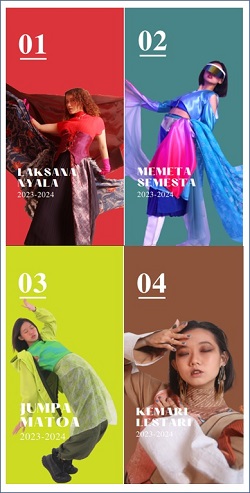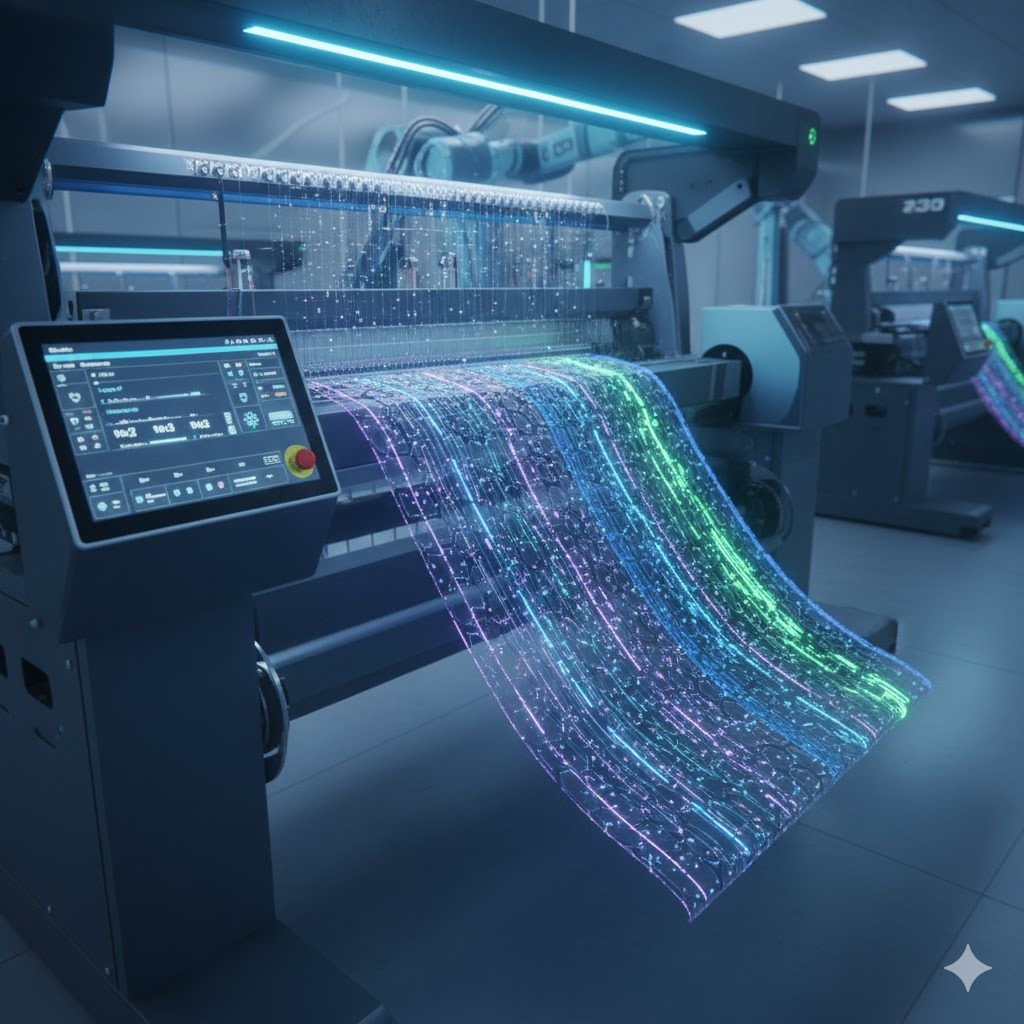Pable, perusahaan daur ulang tekstil lokal berbasis di Surabaya, Jawa Timur, hadir sebagai salah satu pelopor transformasi industri tekstil Indonesia menuju praktik berkelanjutan. Sejak berdiri pada 2020, Pable telah mendaur ulang 270 ton limbah tekstil yang terkumpul melalui berbagai program, seperti “Portable” untuk pembuangan limbah tekstil masyarakat, serta “Uniform Disposal Program” yang menargetkan limbah seragam instansi dan perusahaan.
Program seragam ini lahir dari kesadaran pendirinya, Aryenda Atma, akan budaya instansi yang kerap memproduksi seragam sekali pakai. Selama tiga tahun, Pable berhasil mengalihkan sekitar 22 ton limbah seragam dari tempat pembuangan akhir, setara dengan 110.000 potong pakaian. Melalui kolaborasi dengan perusahaan dan instansi pemerintah, Pable mendorong kesadaran akan pentingnya daur ulang dalam rantai industri tekstil.
Lebih dari sekadar bisnis, Pable menjalin kemitraan dengan komunitas penenun Desa Karangrejo, Jawa Timur. Tradisi tenun lokal dipadukan dengan misi sirkularitas, menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata. Produktivitas komunitas meningkat hingga 22%, mesin tenun kembali beroperasi, dan sistem irigasi desa direvitalisasi. Dengan begitu, Pable tidak hanya mengurangi limbah tekstil, tetapi juga melestarikan budaya sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Namun, tantangan industri tekstil Indonesia masih besar. Meski menjadi produsen tekstil kedelapan dunia, hanya sekitar 12% limbah tekstil yang berhasil didaur ulang setiap tahun. Kesenjangan antara produsen dan konsumen dalam sistem garmen membuat siklus ekonomi belum berjalan utuh. Pable mencoba menutup celah tersebut dengan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular—memanfaatkan kembali limbah untuk memperpanjang umur produk dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru.
Upaya seperti ini sejalan dengan prioritas pemerintah yang tertuang dalam Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025–2045, yang menargetkan pengelolaan limbah tekstil hingga 3,5 juta ton pada 2030. Dengan penerapan prinsip sirkular, potensi dampak ekonomi bisa mencapai Rp19,3 triliun atau sekitar 5,5% PDB nasional.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertekstilan pun semakin relevan. Insentif fiskal, pengembangan SDM, serta perlindungan kekayaan intelektual untuk inovasi tekstil menjadi poin penting yang diusulkan oleh para ahli. Meski begitu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai insentif fiskal saja tidak cukup. Dukungan regulasi yang komprehensif, efisiensi biaya produksi, dan infrastruktur energi juga mutlak dibutuhkan agar industri tekstil kembali kompetitif.
Keberadaan Pable menjadi contoh konkret bagaimana inovasi lokal dapat bersinergi dengan kebijakan nasional. Melalui kolaborasi pentahelix—antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media—masa depan industri tekstil Indonesia berpotensi lebih berkelanjutan, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat global.