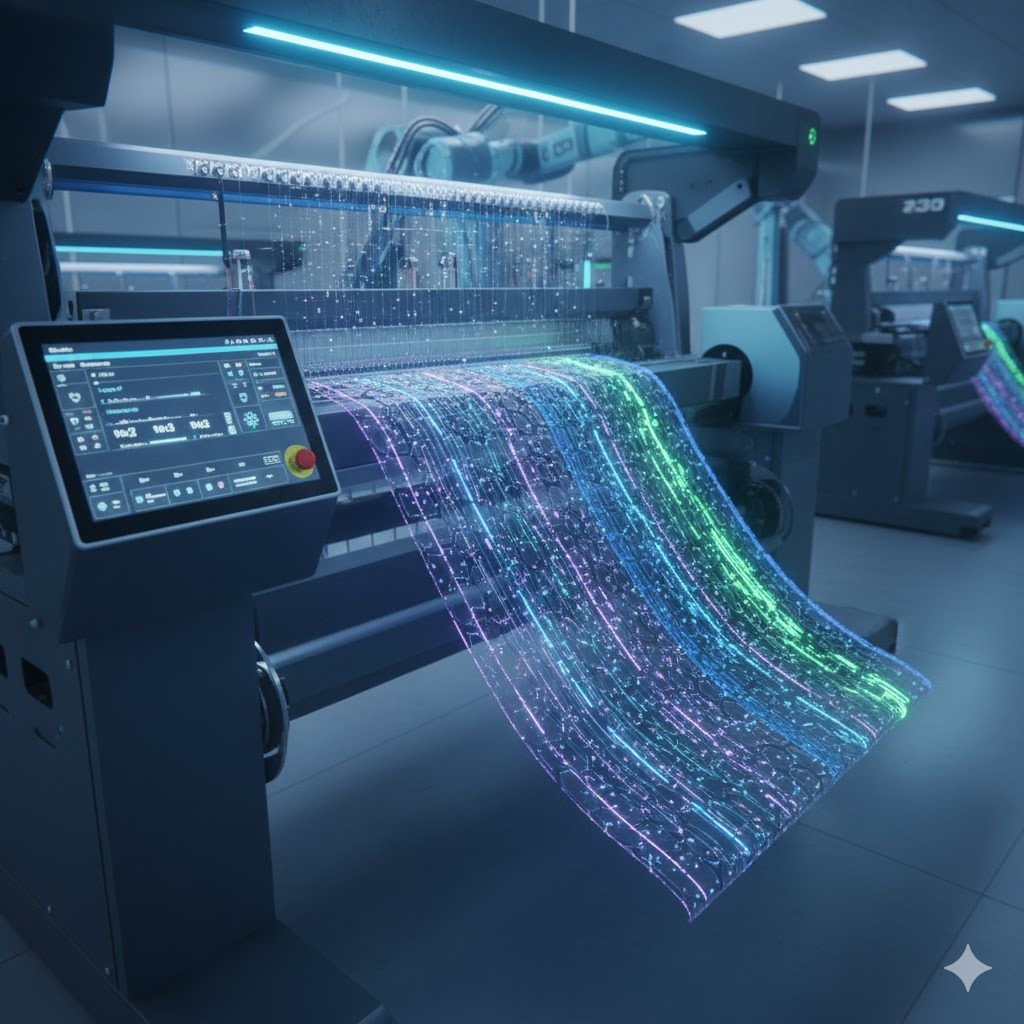Industri tekstil nasional kembali menghadapi tekanan besar akibat derasnya arus impor. Para pelaku usaha mendesak pemerintah agar segera menetapkan pembatasan kuota impor pakaian jadi dan produk tekstil maksimal 50 ribu ton per tahun. Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menyusul gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan pabrik di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Nandi menjelaskan kapasitas produksi dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan domestik. Dari total kapasitas produksi sebesar 2,8 juta ton per tahun, kebutuhan pasar dalam negeri sekitar 2 juta ton bisa dipenuhi tanpa harus bergantung pada produk impor. Bahkan, industri nasional masih mampu menyisihkan sekitar 500 ribu ton untuk ekspor. Ia menekankan pembatasan impor diperlukan agar industri lokal tidak semakin terhimpit oleh masuknya produk asing, baik legal maupun ilegal.
Selain itu, Nandi mendesak Kementerian Perindustrian lebih transparan dalam mengumumkan perusahaan penerima kuota impor beserta besarannya. Menurutnya, keterbukaan sangat penting untuk mencegah terulangnya masalah distribusi kuota seperti yang terjadi pada sektor benang dan kain. Ia menaruh harapan pada penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025, yang mewajibkan importir diverifikasi sebelum mendapatkan kuota impor. Namun, ia menegaskan aturan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya pembatasan kuota yang jelas.
Keresahan serupa turut disuarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA Tekstil). Ketua Umum IKA Tekstil, Riady Madyadinata, mengungkapkan bahwa PHK tidak hanya menimpa operator, tetapi juga tenaga ahli hingga manajemen menengah. Ia menilai pasar yang dipenuhi produk impor dengan harga lebih murah hingga 40 persen menjadi penyebab utama lemahnya daya saing produk lokal, apalagi ditambah tingginya beban biaya produksi di Indonesia.
IKA Tekstil menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki, mulai dari daya saing energi, kualitas SDM, logistik, hingga budaya kerja perusahaan. Di sisi lain, banyak tenaga ahli Indonesia kini justru memilih bekerja di luar negeri karena industri TPT di negara lain sedang berkembang pesat. Riady menilai investasi asing, terutama dari Tiongkok, belum mampu menahan gelombang PHK dan penutupan pabrik, sehingga langkah perlindungan konkret masih sangat dibutuhkan.
Tekanan terhadap industri tekstil sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu. Puncaknya, terjadi saat PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang mempekerjakan sekitar 50 ribu orang resmi menutup pabriknya pada Maret 2025. Situasi serupa kini dialami PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), perusahaan tekstil milik BUMN, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.
Dalam keterbukaan informasi, pengendali perusahaan Tan Heng Lok menjelaskan SBAT sudah berhenti beroperasi sejak Juli 2024. Majelis hakim menunjuk Joko Dwi Atmoko sebagai hakim pengawas serta Asri, Syafrullah Alamsyah, dan Irwandi Husni sebagai kurator pailit. Gugatan PKPU terhadap SBAT sendiri bermula pada akhir 2024 ketika dua perusahaan dan satu individu mengajukan perkara ke pengadilan.
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), sebagai BUMN pemilik 13,996 persen saham SBAT, kini juga terdampak atas keputusan pailit tersebut. Meski demikian, persoalan ini mencerminkan bahwa industri tekstil nasional masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan campur tangan pemerintah. Pembatasan impor dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menahan laju penurunan industri, menjaga lapangan kerja, serta menyelamatkan keberlangsungan usaha tekstil dalam negeri.