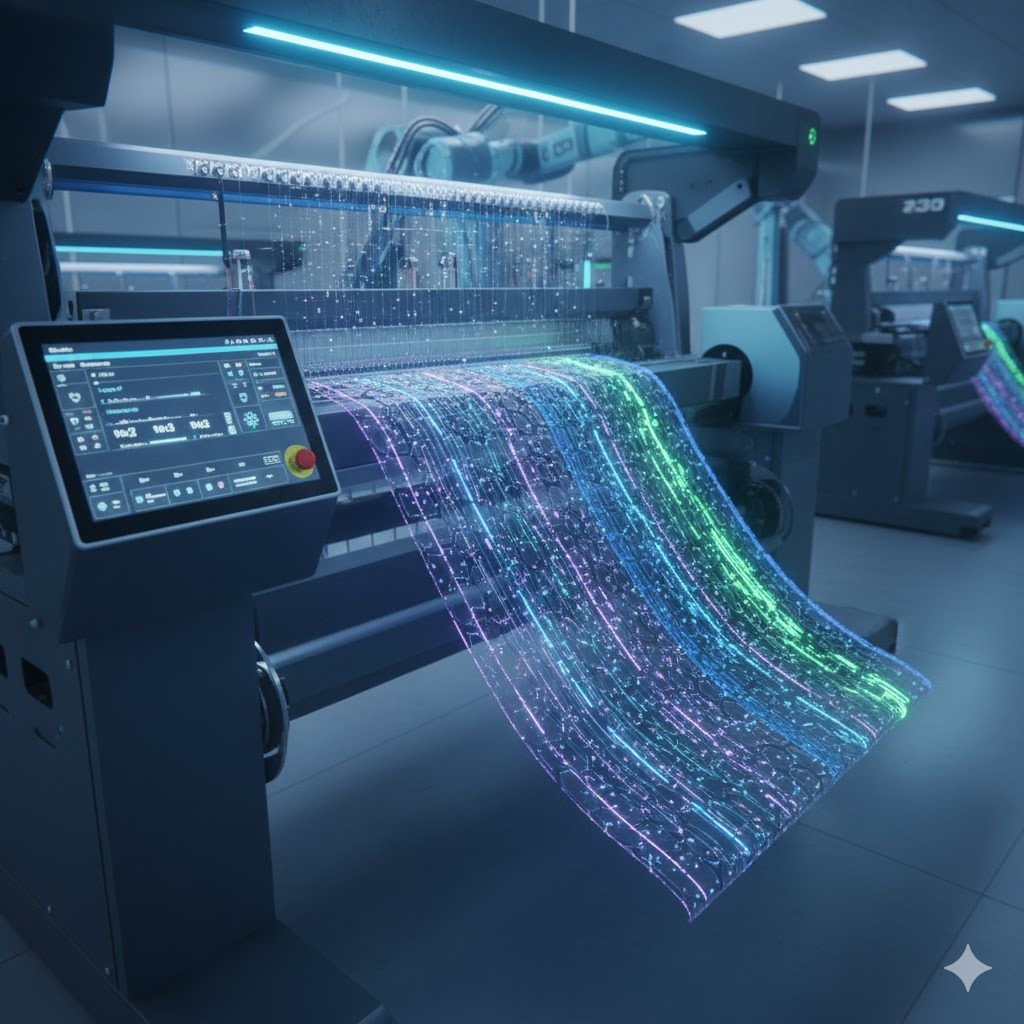Rencana peningkatan pembelian kapas (cotton) dari Amerika Serikat (AS) dinilai sulit direalisasikan di tengah anjloknya utilisasi industri pemintalan dalam negeri. Rendahnya tingkat produksi membuat kebutuhan bahan baku belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, sehingga permintaan impor kapas pun masih tertahan.
Padahal, wacana peningkatan impor kapas dari AS menjadi bagian dari strategi negosiasi perdagangan, khususnya untuk mendorong penurunan tarif produk Indonesia menjadi 19 persen. Namun di lapangan, kondisi industri hulu tekstil belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma G. Wirawasta, menyampaikan bahwa tekanan terhadap industri serat dan benang masih sangat berat. Melemahnya permintaan pasar domestik, ditambah serbuan produk impor, membuat kapasitas produksi pabrik pemintalan tidak berjalan optimal.
“AS meminta kita membeli lebih banyak cotton dari mereka. Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50 persen,” ujar Redma, Rabu (18/2/2026).
Sebelum pandemi, total impor kapas Indonesia tercatat sekitar 600.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 ton dipasok dari AS, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu mitra utama penyedia bahan baku bagi industri tekstil nasional. Saat itu, utilisasi industri relatif stabil sehingga kebutuhan bahan baku pun tinggi.
Namun tren tersebut berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2022, volume impor kapas terus menurun. Hingga 2025, total impor kapas Indonesia hanya sekitar 300.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, porsi impor dari AS menyusut tajam menjadi sekitar 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas produksi di sektor pemintalan.
Menurut Redma, selama tingkat utilisasi belum membaik, hampir mustahil terjadi peningkatan impor kapas dari AS. Dengan kapasitas produksi yang masih berada di bawah 50 persen, pelaku industri cenderung menahan pembelian bahan baku karena persediaan masih mencukupi untuk memenuhi permintaan yang ada.
Ia menambahkan, rendahnya utilisasi bukan tanpa sebab. Industri pemintalan menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya produk impor, baik berupa kain maupun benang jadi, yang masuk dengan harga sangat kompetitif. Bahkan, terdapat dugaan praktik dumping yang membuat produk impor dijual di bawah harga wajar.
Kondisi ini membuat pasar domestik, yang seharusnya menjadi penopang utama industri tekstil nasional, justru tergerus oleh produk luar negeri. Ketika permintaan dalam negeri melemah dan persaingan tidak berjalan adil, pabrik dalam negeri kesulitan meningkatkan produksi maupun menyerap tenaga kerja secara optimal.
Situasi tersebut juga berdampak pada daya tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan. Meski pemerintah berharap peningkatan pembelian kapas dari AS dapat menjadi bagian dari paket diplomasi ekonomi, realisasinya tetap bergantung pada kondisi riil industri di dalam negeri.
Redma menegaskan, perbaikan ekosistem industri menjadi kunci utama. Tanpa perlindungan pasar domestik yang lebih efektif dan pengawasan impor yang ketat, sulit bagi industri pemintalan untuk bangkit dan meningkatkan utilisasi.
“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing, meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” ujarnya.
Dengan kata lain, upaya mendorong kenaikan impor kapas dari AS tidak bisa dilepaskan dari agenda pembenahan industri tekstil nasional secara menyeluruh. Selama utilisasi masih rendah dan pasar domestik belum pulih, ruang untuk meningkatkan pembelian bahan baku dari luar negeri akan tetap terbatas.